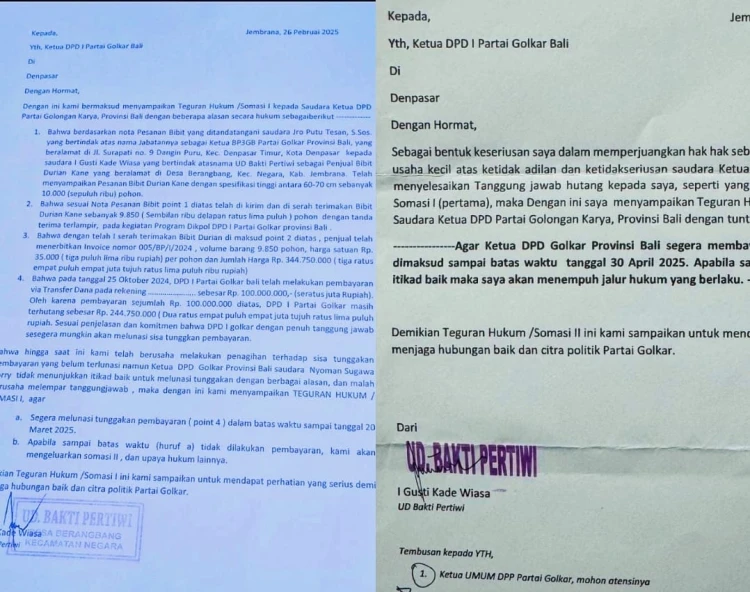Sulinggih Perempuan Dilarang Berbusana Seksi dan Menor! Ini Alasannya.
Minggu, 19 Juni 2016

Baliberkarya/ist
Baliberkarya.com-Denpasar. Tekanan globalisasi membawa dampak terjadinya pergeseran etika dalam berbusana adat ke Pura oleh generasi muda Hindu di Bali. Banyak generasi muda yang kurang memahami dan juga ada yang tidak mau memahami tentang etika dalam berpakaian ke Pura.
Banyak dari mereka terutama kaum perempuan yang memakai model baju kebaya (baju atasan yang sering dikenakan para wanita dalam persembahyangan ke Pura) yang kurang sesuai, dengan bahan transparan dengan kain bawahan (kamen) bagian depan hanya beberapa sentimeter di bawah lutut melakukan persembahyangan.
Begitu pula halnya juga untuk para wiku (sulinggih) dan walaka/pemangku (bukan sulinggih) di dalam berbusana pada saat ke Pura harus juga sesuai dengan etika yang ada. Hal itu disoroti Ida Pedanda Gede Telaga dari Geriya Gde Telaga Sanur dalam Paruman Sulinggih se-Kota Denpasar, Sabtu (18/6/2016) di Wantilan Pura Loka Nata Lumintang. Paruman ini dihadiri Sekda Kota AAN Rai Iswara yang sekaligus menyerahkan kriya patra, kartu anggota sulinggih serta punia.
Menurut Ida Pedanda Gede Telaga, seseorang yang sudah di-dwijati atau di-diksa dalam hal ini sulinggih/wiku, harus mengubah cara-cara berpakaiannya. Mereka tidak boleh lagi berlaku seperti ketika masih dalam status walaka, misalnya memakai celana panjang, memakai celana atau baju jeans, menggunakan perhiasan, tampil menor berpakaian seksi dan lain-lainnya.
Seorang yang sudah didiksa atau dwijati tidak masih berstatus walaka tetapi ia sudah berubah status menjadi Sulinggih atau Pandita. Oleh karena itu, seorang Sulinggih wajib menggunakan pakaian kesulinggihan yang baik seperti, untuk pakaian sehari-hari sulinggih laki-laki (sulinggih lanang) baiknya mengenakan, kain putih, selimut kuning bertepi putih, ikat pinggang putih, keluar rumah (griya) harus memakai tongkat, boleh memakai jubah (kwaca rajeg).
Sulinggih perempuan (sulinggih istri) baiknya menggunakan kain yang dasarnya kuning (boleh berkembang namun warna dasar kuning masih tetap dominan), baju putih, selendang kuning dan ikat pinggang putih. “Busana tersebut yang baik dikenakan oleh para wiku yang ada di Kota Denpasar dan jangan meniru model berbusana budaya agama yang lain dalam berpakaian dengan banyak menggunakan perhiasan dan bentuk pakian yang tidak sesuai” ungkapnya.
Di sisi lain, dijelaskan Ida Pedanda Telaga, walaka (bukan sulinggih) yang dengan kata lain mereka yang belum di-winten ekajati atau mereka yang masih mengabdikan dirinya sebagai masyarakat umum, bukan Pinandita, sarati, atau Pandita di dalam berbusana hendaknya berbusana lengkap serba putih, dari bentuk destar mongkos nangka, baju, kain dan kampuh.
Bagi yang memelihara rambut dimasukkan ke dalam destar dengan cara dikonde, sehingga tidak terurai. Kemudian tidak dibenarkan mengenakan busana pada waktu memuja seperti busana Pandita, termasuk juga dalam hal tatanan dandanan rambut.
Perlengkapan Pamangku dalam melaksanakan tugasnya tidak memakai, perlengkapan sebagaimana yang dipergunakan oleh Pandita. Yang dipergunakan oleh Pamangku adalah genta, dupa sastrat, sangku atau payuk, serta dulang sebagai alasnya, dikarenakan walaka ini merupakan seorang rohaniawan dan sekaligus seorang spiritualis dan sebagai seorang rohaniawan walaka dituntut melaksanakan fungsi manifesnya.
Sementara ketua Sabha Upadesa Wayan Meganada menambahkan pelaksanaan paruman sulinggih se-Kota Denpasar merupakan yang ketiga kalinya, dimana kali ini paruman sulinggih diikuti oleh sulinggih, walaka dari 35 Bendesa Desa Pakraman se-Kota Denpasar.
Dengan tujuan untuk menyamakan tata cara berbusana wiku dan walaka yang baik pada saat ke Pura maupun sehari-hari dalam melaksanakan tugasnya. Supaya hasil dari paruman ini kedepannya bisa diharapkan penyatuan persepsi antara para sulinggih maupun walaka dalam berbusana yang baik dan sepantasnya dalam melaksanakan tugas keagamaan. (bb)
Berita Terkini
Berita Terkini


Berita Terpopuler